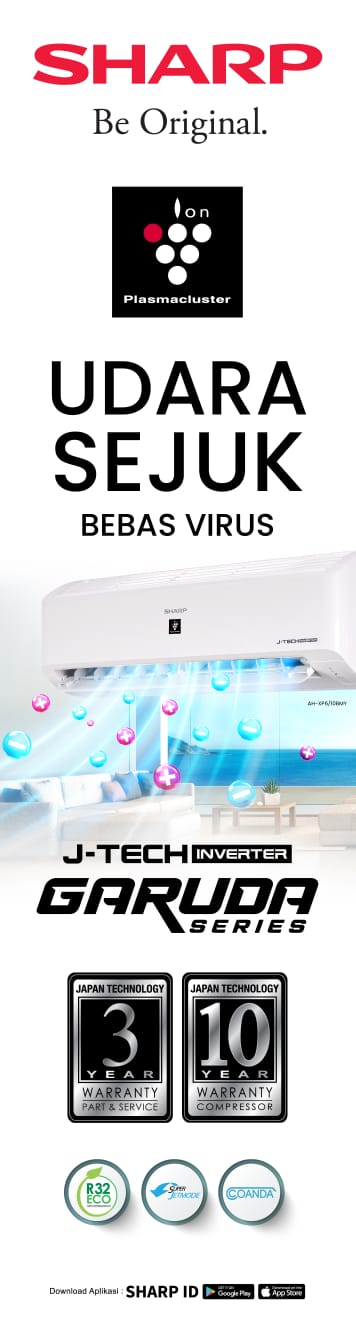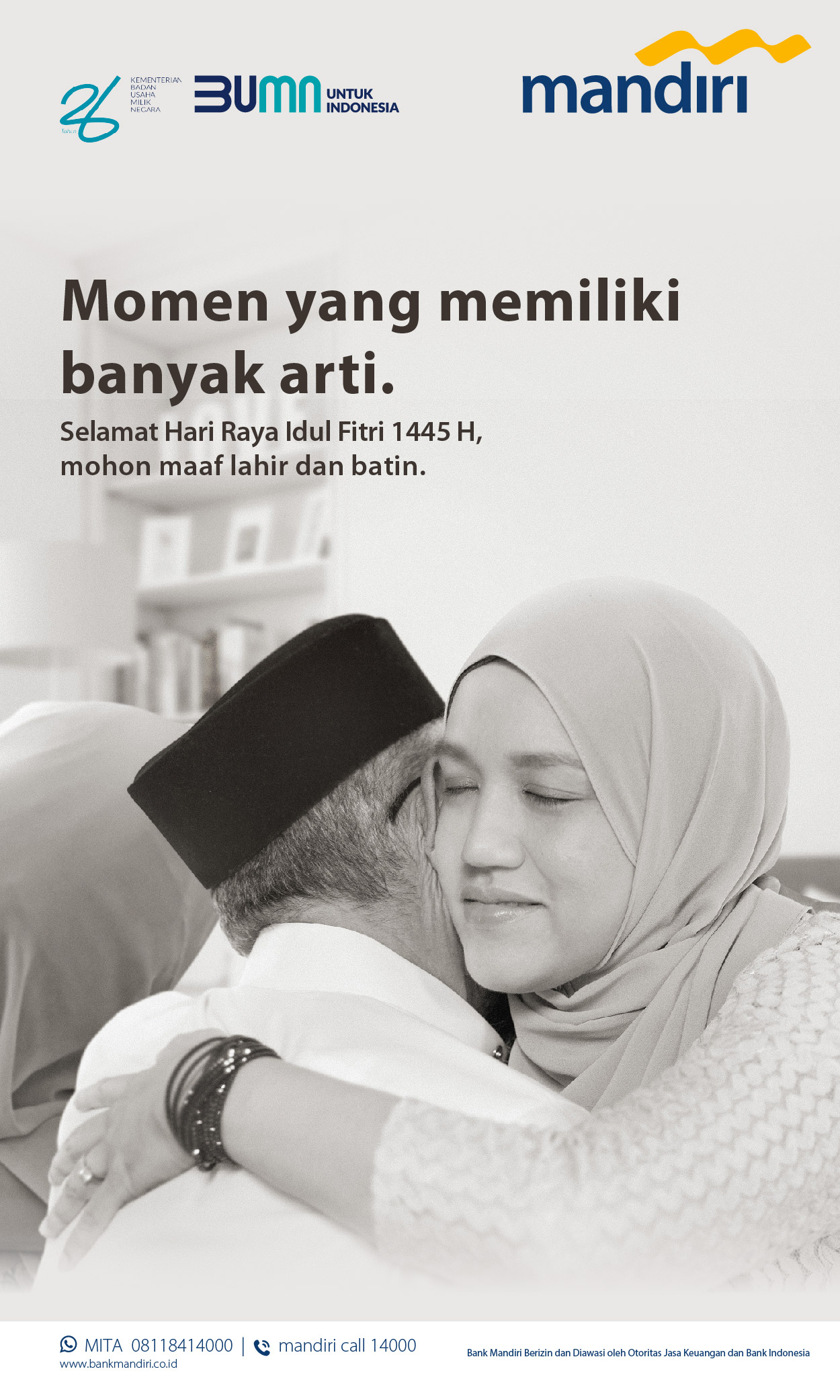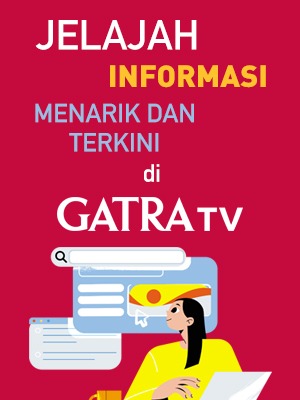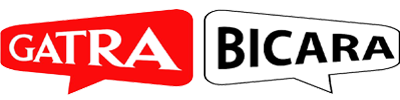Oleh: Alex Yungan *)
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them". - Albert Einstein
Rasionalitas Amputasi Kawasan Hutan
Kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah gagal memenuhi mandat UUD 1945 untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Slogan "hutan untuk kesejahteraan" pada mata uang koin Rp100 tahun 1978 sudah usang dan tidak relevan lagi, sebagaimana mata uang koin tersebut tidak digunakan dan ditinggalkan banyak orang.
Saat ini, menggantungkan harapan agar kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi datang dari hutan dan kawasan hutan semak adalah kesia-siaan dan perlu segera dilupakan. Kawasan hutan negara yang tidak produktif harus segera diamputasi!
Kontribusi rata-rata sektor kehutanan terhadap PDB nasional selama lebih dari satu dekade terakhir (2010-2022) tidak pernah lebih dari 1%, hanya 0,71%.
Bahkan, tahun 2022 kontribusi dari sektor ini hanya 0,60% atau setara dengan Rp118,39 triliun (BPS 2023).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa kontribusi dari sektor kehutanan tersebut "almost nothing" dan "it doesn’t sound right" (Kompas 28 Juni 2022).
Sektor kehutanan dengan rezim "kawasan hutannya" yang menguasai daratan begitu luas --- mencapai 120,3 juta hektar (MoEF 2020) --- telah menjadi sangat tidak produktif dibandingkan dengan sektor lain seperti perkebunan kelapa sawit.
Sektor perkebunan tersebut yang hanya menguasai lahan seluas 16,83 juta hektar (Ditjenbun 2023), atau sekitar 13,99% dari total luas kawasan hutan, selama lebih dari satu dekade terakhir menyumbang rata-rata sekitar 3,64% terhadap PDB nasional.
Tahun 2022, sektor perkebunan kelapa sawit menyumbang sekitar 3,76% bagi PDB nasional atau setara dengan Rp735,91 triliun (BPS 2023).
Celakanya, kini, sektor kehutanan memaksa sektor-sektor produktif lainnya seperti perkebunan kelapa sawit, untuk mengikuti jejak kegagalannya itu di bawah rezim kebijakan "kawasan hutannya".
Kebijakan yang begitu menghambat dalam taraf yang tidak dapat diterima akal sehat bagi kemajuan sektor-sektor produktif tersebut, melalui kerumitan mekanisme perizinannya yang kompleks (Hermosilla dan Fay 2005; Wibowo et al. 2019) dan mensyaratkan biaya transaksi yang tinggi (Kartodihardjo et al. 2015).
Implementasi kebijakan kehutanan selama lebih dari satu dekade terakhir sejak diterbitkannya UU 41/1999 adalah sangat aneh (oddest).
Pertama, pertumbuhan signifikan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan dianggap lebih sebagai tindakan penyerobotan dari pada akibat ketidakpedulian dan kesombongan KLHK yang telah gagal menjaga "rumah"-nya sendiri.
Kedua, penelantaran kawasan hutan yang diduga dilakukan secara sengaja tersebut dapat mengisyaratkan motif ekonomi dibaliknya, dengan demikian, sengaja dibiarkan untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari.
Dengan menggunakan sejumlah asumsi rasional dalam analisisnya, diperkirakan bahwa penelantaran kawasan hutan seluas 3,4 juta hektar yang akhirnya diketahui menjadi sawit itu, memiliki nilai manfaat ekonomi dari CPO sekitar Rp131,64 triliun.
Bila seluruh kawasan hutan tersebut dimanfaatkan untuk produksi biodiesel, nilai manfaat ekonominya diperkirakan sekitar Rp61,79 triliun.
Namun bila pemanfaatan kawasan hutan tersebut diasumsikan 50% untuk memproduksi CPO dan 50% untuk biodiesel, maka benefit ekonomi yang didapatkan diperkirakan sekitar Rp96,72 triliun.
Hasil analisis seperti diuraikan tersebut dapat mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, potensi nilai manfaat dari luasan kecil pengelolaan sawit di dalam kawasan hutan tersebut ternyata jauh melampaui nilai PDB sektor kehutanan dalam satu dekade terakhir.
Artinya, ratusan juta hektar kawasan hutan negara di bawah rezim kebijakan "kawasan hutan"-nya KLHK itu telah gagal sama sekali untuk mewujudkan mandat UUD 1945 yaitu "untuk mencapai sebesarbesar kemakmuran rakyat", yang seharusnya nilai ekonomi yang dihasilkan jauh melampaui nilai potensi dari hasil analisis sebagaimana yang dikemukakan.
Kedua, ada nilai potensi ekonomi yang diduga sengaja dibiarkan hilang begitu saja dari operasionalisasi sawit dalam jumlah besar, sedikitnya seperti hasil analisis yang disampaikan.
Ketiga, anehnya, KLHK terkesan merasa puas dan bangga dengan potensi pendapatan negara yaitu PNBP dari denda administratif kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan sebesar Rp50 triliun (DPR RI 2023), yang seharusnya nilai ekonominya itu dapat jauh lebih besar dari estimasi sebagaimana yang telah disebutkan apabila kebijakan pengelolaan kawasan hutan negara dikembangkan dan dilakukan secara produktif dan bertanggung jawab oleh KLHK. This cannot be true and deserves to be questioned!
Keanehan berikutnya yaitu terjadi dalam hal mekanisme pengenaan denda administratif yang diberlakukan pemerintah (KLHK) kepada para pihak, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Penegakan hukum di dalam implementasi kebijakan kehutanan tidak dilakukan secara adil dan imparsial yaitu tidak ada lembaga/institusi negara yang memiliki kriteria yang sama dengan yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang terjadi akibat perkebunan kelapa sawit yang diproses secara hukum.
Padahal, nyatanya kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh KLHK sendiri, karena ketidakpedulian dan kebijakan pembiarannya.
Pihak sebenarnya adalah korban dapat dihukum dengan denda administratif, kecuali lembaga pemerintah itu sendiri yaitu KLHK.
Siapa yang harus bertanggung jawab atas penelantaran dan pembiaran secara sengaja pada kawasan hutan yang rusak yang diklaim sebagai hutan lindung (HL) dan hutan konservasi (HK)? Kedua jenis fungsi penggunaan lahan tersebut dapat dikatakan sepenuhnya dikelola oleh KLHK.
Ketidakpedulian, penelantaran dan pembiaran pada kedua tipe fungsi penggunaan lahan tersebut yang telah secara sengaja dilakukan oleh KLHK, sehingga membuat kawasan tersebut menjadi rusak, dan akhirnya menjadi tidak berhutan, sama sekali tidak berbeda dengan pembukaan kawasan hutan (yang belum tentu berhutan) untuk kebun sawit yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi pada kawasan hutan lainnya dengan fungsi lainnya itu.
Seandainya hukum diberlakukan secara imparsial, dengan menerapkan logika dan cara perhitungan yang sama seperti yang diberlakukan pemerintah kepada para korporasi sawit sebagaimana dituangkan di dalam Lampiran PP 24/2021, maka pekerjaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menjadi semakin ringan.
Artinya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, hanya perlu memantau KLHK untuk meningkatkan pendapatan negara.
Akibat penelantaran dan pembiaran yang diduga secara sengaja dilakukan oleh KLHK sehingga menyebabkan 33,4 juta hektar kawasan hutan Indonesia menjadi rusak, tidak berhutan atau tidak produktif (unforested), maka KLHK harus menyetor ke kas negara paling sedikit sebesar Rp1.616,02 triliun hingga Rp15.858,63 triliun sebagai denda administratif.
Jika KLHK mengklaim bahwa hanya HK dan HL sebagai kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya, maka KLHK perlu menyediakan anggaran sebesar Rp488,67 triliun hingga Rp4.795,57 triliun.
Perlu dicatat bahwa, nilai tersebut hanya berasal dari kerugian fungsi produksi, diasumsikan sebagai kehilangan pendapatan bersih dari penjualan kayu Akasia atau CPO, dari pembiaran kawasan hutan rusak sejak lama yang seharusnya dapat segera dibuat menjadi produktif.
Kerugian lainnya, seperti dari fungsi jasa ekosistem hutan, kerugian moril dan psikologi akibat konflik tenurial yang berkepanjangan dan lain sebagainya, belum diperhitungkan.
Idealnya, hukum yang disimbolkan dengan Lady of Justice, menggambarkan persamaan di depan hukum, tetapi dalam kenyataannya hukum adalah buta terhadap keadilan.
Penegakan hukum kepada sejumlah pihak yang dianggap telah merusak hutan dengan cara membayar denda administratif berupa PNBP kecuali KLHK, adalah jelas-jelas tindakan yang bersifat politis.
Kebijakan seperti ini tampaknya lebih ditujukan untuk membunuh sektor-sektor produktif dibandingkan mendidik sektor-sektor tersebut menjadi lebih berkemajuan.
Pendekatan dan praktik-praktik hukum seperti ini sangat tidak baik dan merugikan penegakan hukum dalam jangka panjang (Soedomo dan Risdiyanto 2020).
Implikasi Kebijakan Amputasi Kawasan Hutan
Apa yang akan terjadi jika kawasan hutan negara yang rusak tidak produktif (unforested) itu diamputasi, dibangun perkebunan kelapa sawit?
Hasil analisis berikut mengilustrasikan apa yang akan terjadi jika kawasan hutan negara yang rusak (unforested) tersebut diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Kebijakan amputasi kawasan hutan negara, terutama perlu dilakukan di kawasan hutan dengan fungsi HP, HPT, dan HPK seluas 23,3 juta hektar melalui perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
Sementara itu, kawasan hutan dengan fungsi HK dan HL seluas 10,1 juta hektar tetap dipertahankan keberadaannya untuk dipulihkan dengan potensi biaya pemulihannya diperoleh dari benefit yang akan ditimbulkan oleh kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan yang terjadi di HP, HPK dan HPT.
Jika kebijakan amputasi ini dijalankan, maka manfaat ekonomi langsung dari CPO (Crude Palm Oil) diperkirakan dapat mencapai Rp888,12 triliun.
Apabila kebijakan produksi CPO ini dikombinasikan dengan biodiesel, misalnya 50%:50%, maka potensi nilai ekonomi yang akan diperoleh sekitar Rp652,50 triliun.
Selain itu, potensi nilai ekonominya diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp416,88 triliun apabila sepenuhnya diarahkan untuk memproduksi biodiesel.
Lalu, jumlah tenaga kerja yang akan diserap dari pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 23,3 juta hektar dari kawasan hutan produksi yang rusak tidak produktif (unforested) tersebut diperkirakan sebanyak ± 2.330.000 orang.
Kebijakan amputasi ini juga dapat memperkuat agenda kebijakan iklim global dan kebijakan kelestarian lingkungan yang telah dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri.
Sedikitnya, dengan asumsi bahwa pemerintah dapat mengatur nilai ekonomi dari hasil keuntungan produksi CPO sebesar 25%-30%, maka pemerintah dapat membangun atau merehabilitasi hutan seluas 8,77 juta hektar - 10,52 juta hektar.
Artinya, pemulihan dan rehabilitasi hutan yang rusak (unforested), yang berada di kawasan hutan konservasi (HK) seluas 4,5 juta hektar dan hutan lindung (HL) 5,6 juta hektar dapat terpenuhi, tanpa ada biaya sedikitpun yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah.
Selain itu, dengan benefit ekonomi dari kebijakan amputasi ini, pemerintah juga dapat memenuhi target rehabilitasi mangrove seluas 1.250 hektar per tahun hingga 2024, dimana seluas 637.000 hektar dari 3,3 juta hektar hutan bakau di seluruh Indonesia mengalami degradasi (MoEF 2020).
Kontribusi dari rehabilitasi hutan yang dihasilkan dari implementasi kebijakan amputasi ini juga dapat mereduksi emisi karbon secara signifikan.
Kontribusi rehabilitasi hutan seluas 8,77 juta hektar - 10,52 juta hektar tersebut diperkirakan dapat mereduksi emisi (sekuestrasi karbon) sebesar 3.985.248.154 tCO2e – 4.782.297.785 tCO2e.
Nilai reduksi emisi ini diperkirakan dapat mencapai target penurunan emisi NDC Indonesia tahun 2030 di sektor FOLU (target CM1 NDC 17,4% = 500 juta tCO2e dan CM2 NDC 25,4% = 729 juta tCO2e), meningkatkan indeks biodiversity dan memperkuat tercapainya target kebijakan FOLU Net Sink 2030 di Indonesia.
Terakhir, pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang tidak produktif dan telah tidak berhutan (unforested) seluas 23,3 juta hektar di HP, HPT dan HPK itu dapat meningkatkan stok karbon dan serapan emisi karbon wilayah dibandingkan dengan kawasan hutan tersebut dibiarkan terlantar begitu saja sebagai semak belukar dan lahan terbuka.
Hasil analisis menunjukkan bahwa, stok karbon dapat meningkat sebesar 1.042.656.360 tC sampai dengan 1.827.514.530,00 tC atau setara dengan peningkatan penyerapan emisi karbon sebesar 3.826.548.841 tCO2e sampai dengan 6.706.978.325 tCO2e.
Akhirnya, apakah KLHK masih tetap bersikukuh keras dengan rezim kebijakan "kawasan hutannya" yang jelas-jelas telah terbukti sangat tidak produktif dan gagal untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat?
Pesan Utama Bagi Para Pembuat Kebijakan dan Para Pihak Terkait
Sedikitnya, selama satu dekade terakhir, pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit yang sangat produktif telah dinilai oleh banyak pihak secara tidak obyektif dan secara sepihak.
Pelabelan negatif mulai dari penyebab deforestasi, hilangnya biodiversitas flora dan fauna, pengabaian hak-hak masyarakat dan lain sebagainya itu, sepenuhnya telah dialamatkan terutama kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Begitu banyak waktu dan sumber daya yang telah terbuang secara sia-sia dan tidak produktif.
Berbagai narasi telah banyak dibangun dan dikembangkan oleh para pihak, baik pihak pro dan pihak kontra, yang kesemuanya itu pada akhirnya berujung di “nilai mata uang rupiah” atau “nilai mata uang dolar Amerika”.
Perhatian serius para pihak untuk mengarahkan perkebunan kelapa sawit agar benar-benar menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan belum pernah benar-benar dilakukan.
Penegakan hukum yang disimbolkan dengan Lady of Justice di dalam implementasi kebijakan kehutanan tidak dilakukan secara adil dan imparsial dan tampaknya penerapannya lebih ditujukan untuk membunuh sektor-sektor produktif, seperti pekebunan kelapa sawit, dibandingkan mendidik sektor-sektor tersebut menjadi lebih berkemajuan.
Selama ini, segala kehebohan yang terjadi di balik polemik dan perdebatan seputar kelapa sawit menyimpan motif masing-masing di dalamnya. Imbasnya, persoalan yang sebenarnya begitu dekat dengan mata penglihatan seringkali menjadi terabaikan.
Satu hal yang pasti adalah, menggantungkan harapan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi kepada hutan dan kawasan hutan semak yang telah tidak berhutan perlu segera ditinggalkan.
Memahami konsep kelestarian sebagai “lebih baik mengkonservasi kawasan hutan terlantar sebagai semak belukar atau lahan terbuka dibandingkan dengan menjadikannya produktif seperti misalnya dengan membangun perkebunan kelapa sawit di dalamnya atau tindakan produktif serupa lainnya” adalah konsep kelestarian picik dan bersifat menjajah yang seharusnya itu sudah tidak berlaku bagi manusia-manusia Indonesia maju.
Oleh karena itu, kawasan hutan yang sudah begitu lama tidak produktif dan tidak berguna itu perlu segera diamputasi, dicari alternatif penggantinya agar semuanya selamat.
Sawit adalah salah satu sektor ekonomi produktif yang telah teruji prestasi dan konsistensinya, baik untuk ekonomi dan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Oleh karenanya, sektor ini perlu diberikan waktu yang cukup, perhatian dan mendapatkan prioritasnya agar dapat tumbuh maksimum sehingga dapat menebarkan pesonanya secara penuh dengan dukungan dan perhatian dari manusiamanusia maju Indonesia sehingga menjadi lebih terarah, dengan demikian memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan tujuan UUD 19945 yaitu “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Singkatnya, amputasi kawasan hutan negara perlu segera dilakukan, bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa tetapi juga generasi manusia-manusia maju Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang!
*)Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL), IPB University.





_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)